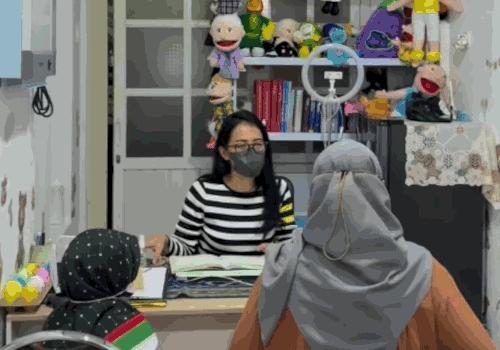Editor: Agung Muhammad Fatwa

Ilustrasi berita kesehatan hoaks. Shutterstock/dok
Oleh dr. Melati Arum Satiti, SpA, MSc*
Pada rezim Orde Baru terjadi gerhana matahari di Indonesia, tepatnya pada 11 Juni 1983. Fenomena alam tersebut merupakan peristiwa yang menakutkan karena pemerintah yang berkuasa menyatakan gerhana matahari dapat menimbulkan kebutaan. Oleh karena itu, ketika terjadi gerhana matahari, masyarakat menutup jendela rumah mereka.
Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, kini pemerintah tak lagi bisa memonopoli dan mengendalikan informasi. Pada era reformasi ini, masyarakat bisa mencari informasi dengan mudah. Masyarakat saat ini telah mengetahui fakta bahwa gerhana matahari dapat menimbulkan kebutaan hanya jika dilihat secara langsung.
Sayangnya, kemudahan akses informasi ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks. Pada 9 Maret 2020, misalnya, ketika pemerintah mengumumkan jumlah kasus COVID–19 bertambah 13 orang, akan muncul berita-berita hoaks yang menambah keresahan masyarakat.
Hoaks atau berita bohong tersebut kemudian dapat menyebar secara lokal hingga global hanya dalam hitungan detik. Oleh sebab itu, sejalan dengan semakin mudahnya persebaran informasi, semakin besar pula tantangan kita untuk dapat memilah informasi yang benar. Untuk itu, berikut ini beberapa cara yang perlu masyarakat ketahui untuk menyaring informasi kesehatan yang valid.
Kenali Latar Belakang Penulis atau Narasumber
Siapa saja bisa dengan mudah menulis dan menggunggah tulisan mereka melalui internet. Oleh karena itu, ketika membaca artikel atau informasi di dunia maya, kita perlu mengetahui apakah penulisnya memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi tersebut. Hal ini bisa diketahui dengan melihat latar belakang pendidikan penulis. Semakin spesifik latar belakang pendidikannya, semakin ahli ia di bidang tersebut.
Sebagai contoh, dokter umum (DU) dan dokter spesialis anak (DSA) dapat menulis atau menjadi narasumber mengenai COVID–19 pada anak. Namun, bila melihat latar belakang pendidikan, DSA lebih mumpuni untuk membahas masalah COVID pada anak. Walapun DU juga mempelajari kesehatan anak pada masa pendidikannya, DSA memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan DU. Hal ini secara resmi telah diakui oleh Konsil Kedoketran Indonesia (KKI).
Dokter spesialis lain (DSL) juga memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari DU. Namun DSL tidak mempelajari ilmu kesehatan anak. Dalam hal ini DSL memiliki kompetensi yang berbeda dari DSA. Dokter umum atau dokter spesialis lain dapat menjadi penulis atau narasumber bila mereka adalah bagian dari tim yang sedang menangani atau pernah mengikuti pelatihan penanganan COVID–19 pada anak. Namun, DSA tetap dianggap lebih mumpuni karena sudah mendapatkan pendidikan dan melewati uji kompetensi mengenai ilmu kesehatan anak.
Selain para ahli dan peneliti, narasumber lain yang juga dapat dijadikan referensi adalah pasien atau penyintas. Misalnya, dalam kasus penyebaran informasi terkait COVID–19, pasien yang baru terdiagnosis COVID–19 memiliki kecenderungan untuk mencari tahu bahwa mereka tidak sendirian. Oleh sebab itu, pasien atau penyintas COVID–19 dapat menjadi narasumber mengenai perjuangan melawan penyakit tersebut.
Bagi pasien atau penyintas, membagi cerita mereka melalui media sosial dapat membuka jalan untuk berbagi pengalaman. Selain itu, cerita keberhasilan dalam melawan penyakit dapat memberikan inspirasi terhadap pasien lain yang baru terdiagnosis. Tentunya, cerita tersebut akan lebih berkesan apabila ditulis melalui sudut pandang pasien sendiri.
Identifikasi Portal Informasi
Saat ini, banyak media mainstream dan media sosial yang menawarkan informasi terbaru. Namun, yang terpenting adalah mencari portal informasi yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, World Health Organization (WHO) dan Center of Disease Control and Prevention (CDC) sering menjadi referensi masalah kesehatan di dunia. Informasi di kedua website tersebut ditulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti orang awam. Selain itu, WHO memberikan informasi perkembangan jumlah kasus COVID–19 di seluruh dunia. Dengan demikian, masyarakat bisa melakukan pengecekan langsung kebenaran jumlah kasus COVID–19 yang diberitakan oleh media lokal.
Bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keterbatasan berbahasa Inggris, informasi yang dibagikan oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) dapat menjadi referensi yang terpercaya. Hal ini karena Kemenkes RI bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden RI dalam bidang kesehatan di Indonesia. Kemenkes RI memberikan informasi perkembangan jumlah kasus COVID–19 di Indonesia melalui press conference di televisi. Detail informasi penderita COVID–19 juga dapat diakses melalui media sosial resmi Kemenkes RI. Selain itu, Kemenkes RI juga menerbitkan protokol penangan COVID–19 yang dapat di unduh dengan mudah oleh masyarakat.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga dapat menjadi referensi untuk siapa saja yang membutuhkan informasi yang lebih spesifik mengenai kesehatan anak. IDAI beranggotakan dokter spesialis anak umum sampai dengan konsultan dari seluruh Indonesia. Selain itu, IDAI sering membagikan informasi mengenai kesehatan anak terutama selama wabah COVID–19 dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam.
Lebih lanjut, sumber informasi mengenai kesehatan anak yang dapat dipercaya adalah American Academy of Pediatrics (AAP). Namun, AAP membagikan informasi dalam bahasa Inggris dengan target pembaca dokter. Oleh sebab itu, dalam tulisan AAP dapat ditemukan bahasa yang sulit dimengerti oleh orang awam. Sebagai solusi, AAP membuat situs Healthy Children yang ditulis menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Healthy Children juga aktif membagikan informasi pencegahan COVID–19.
Telaah Informasi
Menelaah atau melakukan analisis merupakan bagian terpenting dari proses pencarian informasi kesehatan yang valid. Oleh sebab itu, pembaca tidak perlu terlalu panik ketika mendapatkan informasi yang “menakutkan”. Terlebih dahulu, telaah informasi sebaik mungkin. Jika diperlukan, bacalah juga berita dari berbagai sumber.
Sebagai contoh, ketika berbagai media memberikan informasi jumlah kematian akibat COVID–19 lebih dari 3.800 kasus. Ternyata, setelah dikonfimasi melalui laporan WHO, memang betul pada tanggal 9 Maret 2020 ditemukan 3584 kasus kematian akibat COVID–19. Jumlah tersebut memang tidak sedikit dan menimbulkan ketakutan. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa 3.809 kasus kematian tersebut berdasarkan laporan dari seluruh dunia. Setelah dilakukan penghitungan, persentase jumlah kasus kematian dari total kasus COVID–19 sebenarnya hanya sebesar 3,5%.
Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan kembali mengenai angka kematian 3,5% tersebut, terutama terkait lokasi terjadinya kasus kematian akibat COVID–19. Dalam hal ini, pada 9 Maret 2020, WHO melaporkan bahwa angka kematian tertinggi ditemukan di China, yakni sebesar 3123 kasus. Dengan demikian, China menyumbang kasus kematian terbanyak, yaitu sebesar 82% dari total kasus kematian. Sementara itu, angka kematian di luar China dilaporkan sebesar 686 kasus (18%).
Sebenarnya, angka kematian akibat COVID–19 jauh lebih kecil jika dibandingkan SARS–CoV dan MERS–CoV, baik secara lokal maupun global. Angka kematian akibat SARS pada 2003 dilaporkan sebesar 11%, sedangkan angka kematian akibat MERS di tahun 2012 dilaporkan sebesar 34,4%. Selain itu, setelah dilakukan telaah lebih lanjut, angka kematian tertinggi pada ketiga penyakit tersebut didapatkan pada kelompok dengan sistem imun yang lemah, yakni kelompok usia ≥ 60 tahun dan kelompok dengan penyakit penyerta, seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit paru kronik, hipertensi, dan kanker. Oleh karena itu, kelompok dengan sistem imun yang baik diharapkan dapat sembuh dari COVID–19 dengan sendirinya.
Demikian beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari berita bohong atau hoaks terkait kesehatan. Kemudahan akses informasi telah membuat masyarakat dengan mudahnya dapat mencari informasi secara mandiri. Oleh sebab itu, alangkah baiknya bila masyarakat bersikap kritis dalam menyikapi setiap informasi peristiwa. Serupa dengan peribahasa malu bertanya sesat di jalan, menenelan mentah-mentah berita dari sumber yang salah akan membuat kita sesat di jalan pula.
*Dokter Spesialis Anak, Alumni Universitas Indonesia (Master Health Technology Assessment, Universiteit Twente Belanda)
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi tempat penulis bekerja.
Referensi
- Kementrian Hukum dan HAM. Undang–undang republik indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Indonesia: Kementrian Hukum dan HAM. 2004. [diakses pada Maret 2020]. Tersedia di http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2004/uu29-2004.pdf
- British Broadcasting Corporation News. How I recovered from coronavirus isolation. United Kingdom: British Broadcasting Corporation News. 2020. [diakses pada Maret 2020]. Tersedia di https://www.bbc.com/news/av/world-asia-51714162/how-i-recovered-from-coronavirus-and-isolation
- World Health Organization. Coronavirus disease (COVID–2019) situation reports. Geneva: World Health Organization. 2020. [diakses pada Maret 2020]. Tersedia di https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200309-sitrep-49-covid-19.pdf?sfvrsn=70dabe61_4
- World Health Organization. Consensus document on the epidemiology of severe acute respiratory syndrome. Geneva: World Health Organization. 2003. [diakses pada Maret 2020]. Tersedia di https://www.who.int/csr/sars/en/WHOconsensus.pdf
- World Health Organization. Middle east respiratory syndrome coronavirus (MERS–CoV). Geneva: World Health Organization. 2012. [diakses pada Maret 2020]. Tersedia di https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
- Sun P, Lu X, Xu C, Sun W, Pan B. Understanding of COVID–19 based on current evidence. J Med Virol. 2020:1–16. Doi: 10.1002/jmv.25722.
- World Health Organization. Middle east respiratory syndrome coronavirus (MERS–CoV). Geneva: World Health Organization. 2019. [diakses pada Maret 2020]. Tersedia di https://www.who.int/news-room/q-a-detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)